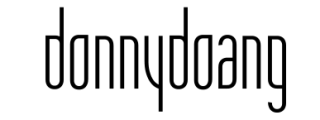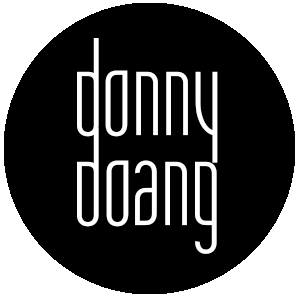0. Pengantar
Tidak dapat dipungkiri, kebudayaan Hindu dari negeri India turut membentuk wajah Indonesia sekarang. Kebudayaan Hindu bukan satu-satunya kebudayaan yang masuk ke Indonesia, masih ada budaya Islam dan Kristen. Namun demikian Kebudayaan Hindu cukup berpengaruh membentuk masyrakat Indonesia, terutama Jawa, Sumatra dan Bali. Pada abad-abad pertama masehi, kebudayaan Hindu masuk ke Indonesai dan mengantar Indonesia pada sistem Kerajaan. Tulisan ini akan mencoba mengulas permasalahan penyebaran kebudayaan Hindu di Indonesia. Ada beberapa kemungkinan tentang siapa yang menjadi pelaku penyebaran kebudayaan Hindu. Memang tidak mudah merekonstruksi sejarah. Namun dengan mengamati kebudayaan Hindu di Indonesai, bisa dicari pendekatan yang paling mungkin.
1. Sejarah Indonesia Pra-Hindu
1.1. Indonesia Prasejarah
Manusia tertua yang masih dapat terpantau ahli sejarah adalah jenis Homo Erectus yang hidup kurang lebih 1,8 juta tahun lampau. Di dusun Ngandong, Mojokerta ditemukan fosil Homo Erectus yang diperkirakan hidup antara 53.0000-27.000 tahun yang lampau[1]. Oleh banyak ahli jenis inilah yang besar kemungkinan berevolusi terus sampai menjadi Homo Sapiens.
Bangsa Indonesia yang terkenal mempunyai keragaman budaya ini diperkirakan berasal dari daratan Asia. Imigrasi dari Asia menyebar ke kepulauan Indonesia. Faktor geografis kepulauan memungkinkan terjadinya perkembangan kebudayaan di masing-masing wilayah. Dengan demikian dapat dimengerti adanya kenyataan keragaman budaya di Indonesia.
Masa sebelum kedatangan bangsa Hindu bagi para sejarahwan menjadi masa-masa gelap. Pada periode ini sangat terbatas sumber-sumber yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk asli kebudayaan kepulauan Indonesia (terutama Jawa, Sumatra dan Bali). Dipakai metode lintas ilmu untuk mencoba meraba-raba keadaan Indonesia sampai dengan abad pertama atau kedua sebelum Masehi. Satu hal yang pasti adalah unsur geografis sangat mempengaruhi bentuk kemasyarakatan yang ada pada waktu itu.
Salah satu hal yang bisa menjadi perhatian adalah budaya bercocok tanam di Indonesia. Bangsa Asia yang menyebar ke Indonesia oleh para ahli dipandang sebagai salah satu penyumbang budaya bercocok tanam, terutama padi. Nampaknya sudah sejak 2.000 tahun lampau, manusia kepulauan[2] mulai mengembangkan budaya bercocok tanam padi dengan sistem yang teratur dalam bentuk sawah. Di kenyataan lain, manusia dataran lebih mengembangkan bentuk ladang. Di daerah kepulauan, nampaknya lebih mudah membuat sistem irigasi teratur, sedangkan daerah dataran memungkinkan bentuk perladangan karena lahan yang tersedia relatif lebih luas.
1.2. Bentuk kemasyrakatan dan agama
Sebelum kedatangan budaya Hindu, di Indonesia jelas sudah ada masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Namun bagaimana mereka hidup dan menata pola hidup bersama adalah hal yang cukup sulit ditelususi. Seperti telah diutarakan diatas, data periode ini sangat minim. Oleh sebab itu dipakai banyak disiplin dipakai, misalnya ilmu bahasa, ilmu purbakala, maupun juga ilmu asal usul bangsa.
Seperti telah diutarakan diatas, ternyata bentuk mata pencaharian bercocok tanam mempunyai pengaruh lansung pada pembentukan tatanan kemasyaraktan Indonesia kuno. Sebagai contoh, dalam masyarakat kepulauan (dibedakan dengan masyarakat pedalaman), bercocok tanam membutuhkan suatu sistem. Karena ada siklus musim hujan dan musim kemarau, maka dibutuhkan pembagian waktu yang pasti[3]. Ilmu perbintangan juga muncul sebagai usaha untuk memastikan saat-saat terbaik untuk menanam dan menuai. Selain itu dibutuhkan pula aturan bersama misalnya dalam pembagian air untuk pertanian. Singkatnya, akhirnya dari sistem tanam padi dapat digali beberapa informasi tentang situasi sebelum kedatangan Hindu.
Oleh para ahli sejarah, hampir dapat dipastikan bahwa sususan masyarakat pedesaan sudah ada sebelum kedatangan kebudayaan Hindu. Susunan desa pada waktu itu agak mirip dengan susunan desa saat ini[4]. Desa adalah suatu bentuk kesatuan kemasyarakatan yang kesejahteraannya ditanggung bersama seluruh warga. Sawah menjadi milik bersama, digunakan demi kepentingan banyak orang. Kepemilikan tanah/ lahan bercocok tanam diperoleh dengan membuka lahan baru di hutan. Namun kepemilikan tersebut masih bersifat terbatas, digunakan demi kepentingan seluruh desa. Jenis kepemilikan inipun bisa hilang dengan bersatunya beberapa desa, misalnya pada masa kerajaan, raja adalah pemilik yang sah atas seluruh tanah. Tradisi ini masih berlanjut setelah ada kebudayaan Hindu. Tanah baru kerap dibuka untuk kemudian dihadiahkan kepada komunitas Hindu maupun Buddha.
Hidup pedesaan tersebut dilengkapi dengan kepercayaan dinamisme maupun animisme. Sebelum agama Hindu dikenalkan, agaknya kepercayaan dinamisme dan animisme sudah berkembang. Dinamisme disini adalah sistem kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di alam[5]. Tiap makhluk hidup mempunyai kekuatan yang berbeda-beda tingkatannya. Dalam perkembangan selanjutnya, juga hidup kepercayaan animisme. Mereka percaya bahwa masing-masing makhluk mempunyai jiwa. Kematian akan memisahkan jiwa dan badan. Jiwa leluhur dihormati karena dipercaya mampu memberi kekuatan bagi yang masih hidup.
2. Tiga Teori Pelaku Penyebaran Kebudayan Hindu di Indonesia
Ada tiga macam teori bebicara mengenai pelaku penyebaran kebudayaan Hindu di Indonesia. Masing-masing teori mempunyai dasar dan juga kelemahan. Boch memaparkan ketiga dalam bukunya[6].
2.1. Teori Kaum Waisa
Teori yang ini mengatakan bahwa Kaum Waisa adalah salah satu golongan masyarakat pelaku penyebaran kebudayaan Hindu di daerah Indonesia. Teori ini berangkat dari fakta kemampuan Kaum Waisa, sebagai golongan pedagang, untuk mencapai daerah-daerah yang jauh demi mendapatkan keuntungan. Hal ini bisa diperkuat dengan ditemukannya jalur-jalur perdagangan dunia pada masa lampau yang ternyata sangat panjang, melintasi samudera dan benua. Selain itu, para ahli yang mengusulkan teori ini juga berangkat dari kenyataan bahwa kebudayaan Hindu di Indonesia ternyata disebarkan dengan jalan damai, bukan suatu intervensi yang bersifat politis. Kaum Waisa “mendarat” di kepulauan Indonesia dengan tujuan perdagangan, dan sangatlah mungkin interaksi yang terjadi dengan penduduk asli Indonesia menjadi jalan penyebaran kebudyaan Hindu.
Namun demikian, ada pula beberapa keberatan atas teori Kaum Waisa ini. Faktor sosiologis dan geografis menjadi alasan untuk mempetimbakan kembali teori ini. Dari sisi geografis, pada waktu itu daya jangkau para pedagang adalah wilayah pesisir pantai. Pedagang memang bisa masuk sampai ke pedalaman, bila itu ada dalam satu daratan. Namun berbeda halnya dengan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Jalan laut adalah satu-satunya penghubung India dan Indonesia, dan karena itulah, wilayah pedagang adalah wilayah pesisir. Sasaran utama para pedagang yang berlabuh tentunya adalah daerah pesisir laut. Kota-kota pelabuhan menjadi ramai oleh para pedang yang hilir mudik dari cina sampai India. Namun fakta yang terjadi, perkembangan Hindu di Indonesia banyak terjadi di wilayah pedalaman Indonesia[7]. Pusat-pusat kebudayaan Hindi di Indonesia ada di pedalaman Kalimantan, Jawa Barat, Kedu, Prambanan, bahkan di kaki G. Merapi. Memang ada dua jawaban yang bisa diajukan: atau para pedagang memang banyak melakukan ekspedisi ke padalaman, atau golongan penguasa waktu di pedalaman mendapatkan akses lansung dengan para pedagang di pesisir.
Secara sosiologis, besar kemungkinan para pedagang ini mempunyai pengaruh kuat sampai pada lingkungan penguasa. Kebudayaan Hindu yang berkembang di Indonesia tidak cukup hanya diperkenalkan oleh para pedagang. Para pedagang ini tidak mempunyai pengaruh cukup kuat dalam hal hidup keagamaan, bahasa, maupun kesenian, kesusasteraan maupun pemerintahan[8].
2.2. Teori Kaum Ksaria
Teori lain mengatakan bahwa kaum ksatria dipandang sebagai kelompok yang paling dominan dalam menyebarkan kebudayaan Hindu dari daratan India. Dalam rekontruksi para ahli sejarah yang mengajukan ini, yang pertama-tama datang dan membawa kebudayaan Hindu adalah kaum Ksatria.
2. 2.1. Analisa
Pertama, di Jawa ada sebuah pola dalam kisah Panji Jawa, yang berkisah tentang kedatangan seorang kaum Ksatria sabrang, yang digambarkan sebagai pihak jahat, datang dan melakukan usaha penaklukan Jawa. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mendirikan kekuasaan di Jawa, salah satunya dengan perkawinan dengan putri Jawa. Maka disebutkan para Ksatria tersebut punya andil besar dalam pembentukan dinasti Raja Jawa.
Kedua, analisa yang lain melihat penyebaran kebudayaan Hindu sebagai salah satu usaha kaum Ksatria di India melebarkan kekuasaan. Kebudayaan Hindu yang disebarkan kaum Ksatria dipandang sebagai hasil dari usaha ekspansi kerajaan Hindu. Istilah “kolonisasi” mungkin bisa menjelaskan fenomena ini. Berhubungan dengan ini, ada pula penjelasan penyebaran kebudayaan Hindu sebagai salah satu pergerakan politis. “Kolonisasi” tersebut ada kemungkinan adalah akibat dari adanya pergolakan politis di India. Sehingga pihak yang tidak berhasil mendominasi kekuasaan, atau bisa juga pihak yang direbut dominasinya, akhirnya berusaha keluar dari medan perselisihan. Para penguasa yang jatuh tersebut akhirnya menyingkir ke kepulauan Indonesia dan mendirikan kekuasaannya.
2. 2. 2. catatan kritis
Teori ini juga mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Dilihat dari bentuk kebudayaan Hindu di jawa. Dalam pandangan para ahli, kebudayaan Hindu di Jawa ternyata mempunyai unsur khas Jawa sangat kuat. Maka gambaran kolonisasi menjadi sulit diterima karena budaya yang Hindu di Jawa nampaknya diterima dengan penuh keterbukaan dan bahkan mengalami percampuran dan perkembangan.
Ada beberapa alasan praktis pertama, tidak pernah ada pergolakan politis yang tercatata dalam sejarah yang mempunyai dampak sampai menyingkirkan sejumlah golongan ksatria tertentu untuk membentuk kerajaan di Indonesia. Apabila memang ada perubahan politis (dan tidak tercatat dalam sejarah India) maka Kaum Ksatria yang berhasil mendirikan kerajaan di Indonesia tentunya akan ada prasasti yang mengatakannya. Dalam situasi semacam itu, biasanya kelompok yang pergi ke tanah asing (dan berhasil melaksanakan penaklukan) akan membuat prasasti yang mengatakan bahwa meraka masih punya keterkaitan dengan daerah asal, dalam hal ini tentunya bangsa India.
Kedua, bila Ksatria seberang berhasil melebarkan kuasa dengan cara perkawinan, tentunya ada keturunan Kaum Ksatria tersebut yang masih ada[9]. Tak pernah ditemukan dalam bangsa Indonesia keturunan suatu suku bangsa yang mempunyai ciri fisik seperti bangsa Dravida di India.
Ketiga, dilihat dari bahasa, teori Kaum Ksatria juga mempunyai kelemahan. Telah diterima umum, pada masanya, Kaum ksatria memakai bahasa dari rumpun Ari, Pakrit dan Tamil. Sangatlah jarang Kaum Ksatria memakai bahasa Sansekerta[10]. Bahasa Sansekerta adalah bahasa yang digunakan dalam upacara-upacara suci maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Kalau memang Kaum Ksatria adalah pelaku penyebaran kebudayaan Hindu, pastilah bukan bahasa Sansekerta yang berkembang di Indonesia. Yang terjadi, dalam bahasa Indonesia (paling tidak Jawa dan Bali) banyak dijumpai kata-kata Sansekerta murni.
Keempat, campur tangan langsung Kaum Ksatria nampaknya tidak nampak pada kebudayaan pola kemasyarakatan Hindu yang masuk dan berkembang di Indonesia. Kaum Ksatria sebagai bangsawan pasti akan membawa sistem kasta dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kasta. Namun di Indonesia tidak nampak dengan jelas pembagian kasta seperti di India. Memang dikenal 4 jenis kasta, namun namun Brahmana malah menjadi kasta yang utama dalam kehidupan di Indonesia. Kalau Kaum Ksatria adalah pelaku penyebaran budaya, tentunya mereka akan menempatkan kaum Ksatria menjadi yang utama. Selain itu, sistem kasta yang ketat tidak muncul dalam pranata sosial praktis, misalnya jabatan pilihan (bukan keturunan), cara makan, penguburan mayat, ritus dan upacara keagamaan.
2.3. Teori Kaum Brahmana
Teori yang ketiga mengungkapkan bahwa, Kaum Brahmana adalah golongan yang paling berpengaruh dalam penyebaran kebudayaan Hindu. Kaum Brahmana yang dimaksud adalah kaum cendekiawan yang memang ahli dalah pengetahuan sastra, ahli kitab, alim ulama Hindu, para filsuf, ahli hukum maupun pemerintahan. Diperkirakan, meraka masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan, bersama-sama dengan kaum waisa. Dengan demikian, teori ini memandang tidak hanya para Brahmana (pendeta) yang melulu berhubungan dengan urusan keagamaan yang menjadi penyebar kebudayaan Hindu.
Gagasan Kaum Brahmana sebagai pelaku utama penyebaran Hindu di Indonesia disampaikan sebagai jawaban atas permasalah dari kedua teori sebelumnya. Kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia hampir dapat dipastikan dilakukan dengan jalan damai. Manusia Indonesia menerima kebudayaan Hindu dengan tangan terbuka dan mempengaruhi Indonesia sampai pada tataran terkecil, sampai pada situasi praktis. Oleh para ahli, hal ini dipandang tidak akan terjadi dengan mulus bila kebudayaan diperkenalkan oleh para penguasa dengan kekuasaannya. Selain itu, Kaum Brahmana dengan leluasa akan masuk ke daerah pedalaman, tidak seperti Kaum Waisa yang ada dalam kepentingan perdagangan.
Salah satu hal yang menjadi pendukung teori ini adalah adanya unsur pengajaran perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Untuk memperjelas, fenomena candi bisa dilihat sebagai contoh. Tak dapat dipungkiri, di Indonesia banyak ditemukan candi-candi peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia, seperti halnya terjadi di India. Namun candi tersebut dapat dikatakan sebagai candi Indonesia asli, walau dihasilkan dalam kebudayaan Hindu, bukan sebuah tiruan dari candi Hindu di India. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa para pembuat candi di Indonesia mengenal betul cara pembuatan candi di India. Nampaknya, para pembuat candi mengenal betul buku-buku pedoman pembuatan candi yang banyak beredar. Buku-buku disebut Cilpacastra adalah panduan tehnis, aturan-aturan dalam seni pahat dan seni bangunan. Dari segi bentuk, walau ada kesamaan konsep, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitek candi di Indonesia adalah orang India, bahkan pimpinan proyekpun tidak. Kalau orang India yang membuat candi (atau merancangnya) pastilah menonjol kesamaan-kesamaan bangung di India dan di Indonesia. Yang menarik perhatian adalah bahwa walaupun pembuat candi Indonesia tidak berkontak langsung dengan candi di India, namun mereka mengerti betul teori membuat candi.
Ada unsur teori maupun pengajaran dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu di Indonesia. Penyebaran dengan unsur pengajaran hanya mungkin terjadi dilakasanakan oleh kaum cendekiawan. Dengan menampilkan teori ini, para ahli membuat jawaban atas kekhasan Hindu di Nusantara. Kebudayaan tersebut telah berkembang sedemikian khas Indonesia. Proses penerimaan itu dibarengi dengan proses pembelajaran “bahan-bahan” budaya sehingga kebudayaan Hindu tidak melulu milik bangsa asing.
Bosch membuat rekontruksi mengenai bagaimana pelaku penyebaran kebudayaan Hindu. Menurut dia, Hindu yang disebarkan di Indonesia hanyalah salah satu dari sekian banyak aliran di India. Ada beberapa aliran yang dengan caranya sendiri mengajarkan keselamatan melalui pembebasan roh pribadi dan pembebasan kelahiran kembali. Salah satu aliran itu adalah Caiva-Siddhanta (termasuk golongan aliran Civaisme). Besar kemungkinan aliran inilah yang kemudian disebarkan di Jawa dan Bali. Aliran yang disebarkan ini ternyata bukanlah agama rakyat biasa, namun termasuk aliran khusus dengan sifatnya agak tertutup. Para pendeta aliran ini diturunkan turun temurun dan harus melalui banyak proses untuk akhirnya menjadi pendeta. Pendeta ini dipandang sebagai penjelmaan Civa sendiri dalam dunia. Pengaruhnya di lingkungan penguasa bisa dirunut dengan paham raja sebagai jelmaan dewa yang bertugas mengatur ketertiban dunia. Mereka bisa dipandang sebagai salah satu pelaku penyebaran Hindu di Indonesia. Walau jumlah mereka sedikit, tapi cukup berpengaruh di Indonesia dalam kurun waktu abad 4 sampai abad 6.
3. Jejak-Jejak kebudayaan Hindu di Indonesia
Bagian ini akan membahas bagaimana kebudayaan Indonesia mulai berkembang setelah masuknya kebudayaan Hindu. Periode perkembangan kebudayaan Hindu adalah antara abad ke 5 sampai abad ke 15. Sumber yang dipakai adalah sejumlah prasasti yang dikeluarkan pada periode itu.
3. 1. sistem religi
Secara umum, sistem religi sejak awal perkembangan kebudayaan Hindu nampaknya tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Kedua hal ini sepertinya saling terkait dan saling membutuhkan. Para penguasa memperluas pengaruh dengan bantuan pengakuan dari para Pendeta. Demikian juga dengan Kaum Brahmana. Mereka dengan leluasa mengajar dan menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu dalam wilayah yang penguasanya membutuhkan mereka.
Dalam kalangan kerajaan nampaknya telah ada pendeta yang punya kedudukan penting. Mereka bertanggung jawab atas terlaksananya ritus demi kelangsungan pemerintahan Raja dan kesejahteraan seluruh kerajaan. Lahan yang dihadiahkan kepada kaum pendeta ini lalu berkembang menjadi biara-biara. Raja dibantu oleh pendeta mengusahakan keserasian seluruh kerajaan. Pembangunan candi-candi bisa dilihat sebagai usaha memajukan hidup keagamaan, namun juga bisa dilihat sebagai pengesahan otonomi Raja terhadap rakyat.
Di tingkat yang lebih bawah, juga berkaryalah pendeta-pendeta yang mengusahakan keserasian. Desa menjadi unit terkecil yang bisa dilihat sebagai model komunitas umum pada waktu itu. Di desa, ritus-ritus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan demi kepentingan umum. Banyak upacara kuno yang ada sebelum kebudayaan Hindu masuk, dipakai dan dimaknai secara baru dalam kebudayaan Hindu di Indonesia. Salah satunya adalalah kurban kerbau[11]. Kurban Kerbau dilakukan dalam kerangka suatu acara besar, misalnya pembangunan jembatan. Dalam budaya Hindu, tradisi ini dihubungkan dengan Durga Mahisasuramadini, kisah tentang Dewi Durga yang membantai raksasa berwujud kerbau.
Contoh lain adalah pemujaan dewi padi, Sri. Walaupun nama “Sri” berasal dari India, namun mitos mengenai dewi yang memperkenalkan budidaya padi ini dikenal diseluruh pelosok nusantara, bahkan yang sejak awal tidak tersentuh kebudayaan Hindu.
3. 2. Bentuk Kerajaan dan situasi kemasyarakatan
Bentuk kerajaan tidak serta merta terbentuk saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia. Komunitas Desa adalah cikal bakal bentuk kemasyarakatan kerajaan. Bentuk kemasyarakatan desa berkembang menjadi komunitas beberapa desa dalam satu wilayah. Beberapa wilayah desa melakukan integrasi dalam upaya mendapatkan jaminan kesejahteraan bersama. Kumpulan desa ini disebut Wanua. Wanua-wanua ini dikuasai oleh penguasa yang disebut dengan raka atau rakaryan. Dalam Prasasti yang muncul pada abad ke-8 di Jawa tengah, telah disebutkan adanya persaingan antara raka dalam memperluas wilayah wanua dan memperkuat pengaruhnya. Salah satu usaha memperkuat pengaruh adalah dengan menganugerahkan lahan-lahan yang baru dibuka kepada komunitas Hindu. Sebagai gantinya, para penguasa mendapatkan gelar dari para Brahmana. Hal ini bisa dihubungkan dengan pemahaman pendeta sebagai perwujudan Ciwa. Raja dianugerahi gelar (terutama gelar maharaja) untuk memberi perspektif religius dalam kepemimpinannya.
Pengembangan bentuk pedesaan terus terjadi. Abad 14, dalam pidato Pangeran Wengker (pamah Hayam Wuruk) di acara perkumpulan tahunan pemuka desa, disampaikan harapan akan kemajuan kesejahteraan desa dengan adanya pembangunan sarana umum (jalan umum, sistem pengairan, dll). Data ini deperoleh dari tuliasan Negarakertagama. Walaupun sudah ada kalangan penguasa, tetap disadari waktu itu, desa harus tetap diperhatikan dan dimajukan agar mampu menjadi penyangga kehidupan Kerajaan.
Dalam melaksanakan pemerintahannya, seorang raja dibantu oleh para pembantunya. Di tingkat desa, dikenal sebutan pamomong, seorang pegawai raja yang betugas memimpin dan membimbing kehidupan bersama. Selain itu, ada pula kelompok pegawai di sekitar lingkungan keraton maupun kota. Istilah yang sering digunakan adalah mantri (mentri), yang pertama adalah yang ada disekitar raja dan yang kedua adalah mereka yang benar-benar harus berkarya. Mantri yang pertama ini bisa disebut sebagai gelar kehormatan, dan biasanya berasal dari anak-anak raja. Sedangan jenis yang kedua tidak punya relasi kekeluargaan langsung dengan raja, namun mereka diserahi tanggun jawab tertentu (misalnya urusan militer, rumah tangga, gedung, kesenian dsb). Dari lingkungan pegawai kerajaan inilah kemudian berkembang sistem kebangsawanan dalam lingkungan kerajaan. Golongan bangsawan tidak melulu terbatas pada hubungan darah. Sistem kasta memang nampak dalam perkembangan kerajaan namun bersifat sangat terbuka. Sebagai contoh, gelar bangsawa bisa diperoleh karena mempunyai jasa tertentu bagi kerajaan.
4. Kesimpulan
Dari paparan sejarah yang ada dan dari pengamatan kebudayaan yang hidup di jaman Hindu, ditemukan 3 kemungkinan teori mengenai penyebaran kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu di Indonesia memang agak unik sifatnya. Letaknya Indonesia cukup jauh dari India dan berbentuk kepulauan. Kebudayaan Hindu di Indonesia ternyata juga mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan kebudayaan asli.
Tidak mungkin kita kembali ke masa lampau untuk memastikan kebenaran teori. Namun dilihat dari kebudayaan Hindu di Indonesia, kiranya mungkinlah dipilih pendekatan yang agaknya cukup mendekati kenyataan. Metode teori yang ketiga mengenai Kaum Brahmana sebagai pelaku penyebaran kebudaan Hindu agaknya bisa diperhatikan sebagai pendekatan yang lebih memungkinkan. Fakta adanya unsur pembelajaran dan pengembangan kebudayaan Hindu yang terjadi dengan jalan damai menjadi faktor pendukung teori ini.
Sebagai fakta sejarah, haruslah disadari teori Kaum Brahman tentulah bukan satu-satunya metode penyebaran kebudayaan ini. Interaksi para pedagang di pesisir pastilah mempunyai andil tersendiri dalam penyebaran kebudayaan. Konsep kerajaan dan cara pemerintahan besar kemungkinan juga disebarkan oleh kaum Ksatria, karena merekalah praktisi yang paling berpengalaman. Unsur pembelajaran besar kemungkinan memang menjadi metode penyebaran yang cukup berpengaruh. Namun cara yang lain pastilah juga besar kemungkinan terjadi. Sehingga kebudayaan Hindu mendapatkan bentuknya yang khas di Indonesia.
Daftar bacaan:
Bosch, F.D.K. and R.Ng.Poerbatjaraka,
1975, Crivijaya Cailendra dan Sanjayavamca, Jakarta: Bharata, (trans. By Boechri from Dutch)
Bosch, F.D.K. and R.Ng.Poerbatjaraka,
1975, Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia
Hadiwijono, Harun,
1971, Agama Hindu dan Buddha, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
Prijohutomo,
1953, Sejarah Kebudayaan Indonesia jilid 2, Jakarta: J.B. Wolters
Lombard, Denys,
1996, Nusa Jawa Silang Budaya,jilid 1-3,Jakarta: Gramedia.
Sastroprajitno, Warsito
1958, Rekontruksi Sedjarah Indonesia: Zaman Hindu, Jogjakarta: P.T. Pertjetakan Republik Indonesia.
Wojowasito
1953, Sejarah Kebudayaan Indonesia: Indonesia sejak pengaruh India, Jakarta: Siliwangi
Daftar Artikel:
Sharma, Arvind. “Hinduism.” Microsoft® Encarta® 2006, Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
Early Indonesia, Excerpted from Indonesia: A Country Study. William H. Frederick and Robert L. Worden , eds. Washington, DC: Federal Research Division of the Library of Congress, 1992, dalam http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/idtoc.html
Sejarah Indonesia, dalam ,http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah01.shtml
Hindu/Buddhist past in Java, Indonesia, dalam http://www.hindunet.org/
Hindu-Buddhism Period of Indonesia Archaelog,y dalam http://www.arkeologi.net/
Indonesia Indianized Empires, dalam http://lcweb2.loc.gov/
IndonesiaThe Spread of Indian Civilization, dalam http://lcweb2.loc.gov/
Earliest Historical Records, dalam http://users.skynet.be/network.indonesia/index.htm
[1] Tahun 2004 diketemukan fosil baru di Flores, yang berumur kurang lebih 18.000 tahun lampu, dengan ciri fisik yang kecil dan pendek (tinggi sekitar 1 Meter). Jenis ini nampaknya cukup cerdas membuat alat dari batu yang sederhana.
[2] Istilah kepulauan dipakai untuk menterjemahkan coastal people yang diperbandingkan dengan inland people (manusia dataran).
[3] Orang jawa membuat kesatuan waktu: lima hari, selapan hari (35 hari), dst.
[4] Mentawai adalah salah satu contoh desa masa kini yang masih sama dengan sistem desa jaman dulu.
[5] Dalam bahasa jawa, kekuatan itu disebut kasekten, dalam bahasa lain sering disebut mana, gaya
[6] Bosch, F.D.K. and R.Ng.Poerbatjaraka, Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesi, Jakarta: Bharata, 1975
[7] Bandingkan dengan kebudayaan Islam yang tersebar oleh saudagar dan berkembang di kota2 pesisir.
[8] Bandingkan dengan pedagang cina. Sudah lama pedagang cina berkiprah di Indonesia, namun sangat sulitlah mereka menyebarkan kebudayaan.
[9] Alasan ini muncul karena diandaikan, kedatangan ksatria tersebut ada dalam jumlah banyak.
[10] Hal ini bisa dibandingkan dengan keraton di Jawa. Para raja, pangeran dan punggawa akan memakai bahasa jawa halus, tidak pernah memakai bahasa jawa kawi.
[11] Lombard, Denys, Nusa Jawa Silang Budaya,jilid 1-3,Jakarta: Gramedia, 1996, hlm 82.